Kajian Sosiologi Novel Atheis karya Achdiat Karta Mihardja
Kajian Sosiologi Novel Atheis karya Achdiat Karta Mihardja - Atheis adalah sebuah roman
karya Achdiat Karta Mihardja yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada
tahun 1949. Roman yang menggunakan tiga gaya naratif ini
menceritakan kehidupan Hasan, seorang Muslim muda yang dibesarkan untuk
berpegang pada agama, tetapi akhirnya meragukan agamanya sendiri setelah
berurusan dengan seorang sahabat penganut Marxisme–Leninismedan seorang penulis penganut nihilisme.
Achdiat, seorang jurnalis serta redaktur yang
pernah bergabung dengan penyair eksentrik Chairil Anwar dan Partai Sosialis Indonesia, menulis Atheis antara bulan Mei
1948 dan Februari 1949. Bahasa Indonesia yang
digunakannya dipengaruhi oleh bahasa Sunda, dan gaya
penulisannya lebih mirip gaya penulis Minang dari
periode sebelumnya daripada para penulis kontemporer. Terutama membahas mengenai
keimanan, novel ini juga menyinggung hubungan modernitas dan tradisionalisme.
Biarpun Achdiat menegaskan bahwa karya ini dimaksud untuk realis, perlambangan dan hubungan simbolis pernah diusulkan
tentang Atheis.
Terjadi pembahasan yang
cukup panas saat Atheis terbit. Tokoh-tokoh agama,
Marxis-Leninis, dan anarkis menolak novel ini karena kurang menjelaskan
ideologi mereka masing-masing, sementara tokoh-tokoh sastra dan masyarakat
banyak memuji roman ini. Penerimaan baik ini mungkin disebabkan diperlukannya
penyatuan nasional oleh Pemerintah Indonesia. Sebelum tahun 1970, Atheis sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan pada tahun
1972 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; pada tahun 1974 novel ini diadaptasikan menjadi film. Selain menerima penghargaan dari pemerintah pada tahun 1969, Atheis sudah
termasuk dalam UNESCO Collection of Representative Works.
Ringkasan Novel Atheis karya Achdiat Karta Mihardja
Hasan yang lahir di
Panyeredan di keluarga penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah siswa yang lumayan pandai dan tinggal bersama
keluarga dan adik angkat, Fatimah. Seusai masa sekolah, Hasan berusaha untuk
melamar temannya Rukmini untuk menjadi istri. Namun, Rukmini yang mempunyai
kedudukan sosial lebih tinggi, sudah dijanjikan untuk seseorang kaya di Batavia
(sekarang Jakarta). Sebagai
ganti, orang tua Hasan minta agar dia menikah dengan Fatimah. Hasan menolak, lalu
mulai sangat mendalami Islam bersama ayahnya. Dia lalu berpindah ke Bandung untuk
bekerja sebagai pegawai pemerintah.
Di Bandung, Hasan bekerja
untuk pemerintah pendudukan Jepang dan hidup secara asketik; dia sering berpuasa
berhari-hari dan memasukkan tubuhnya ke dalam sungai berulang kali dini pagi.
Saat di Bandung, dia bertemu dengan sahabatnya semasa kecil, Rusli, yang
memperkenalkan seorang gadis bernama Kartini. Karena melihat bahwa Rusli dan
Kartini adalah Marxis-Leninis yang atheis, Hasan merasa seakan dipanggil untuk mengembalikan
mereka ke agama Islam. Namun, dia tidak dapat mengatasi argumentasi Rusli yang
menolak agama, sampai Hasan pun mulai meragukan keimanannya. Lama-kelamaan
Hasan menjadi semakin sekuler, sampai pada suatu hari dia lebih memilih
menonton film di bioskop bersama Kartini daripada sholat Maghrib. Melalui Rusli,
Hasan diperkenalkan dengan berbagai orang yang menganut berbagai macam
ideologi, termasuk Anwar, seorang nihilis yang suka
main wanita; Hasan juga mulai mendekati Kartini.
Pada suatu hari, Hasan
kembali ke Panyeredan bersama Anwar untuk mengujungi keluarganya. Saat di sana,
Anwar melihat dua penjaga malam yang ketakutan dekat suatu permakaman. Ketika
diberi tahu bahwa penjaga malam itu melihat hantu, Anwar masuk ke permakaman
itu bersama Hasan untuk membuktikan bahwa tidak ada hantu di sana. Namun, Hasan
merasa bahwa ada sesuatu yang mengincarnya; hal ini membuat dia melarikan diri
dari permakaman tersebut. Ketika Anwar tertawa atas reaksi Hasan, Hasan merasa
imannya sudah patah. Dia akhirnya bertengkar heboh dengan keluarganya tentang
soal agama, sehingga dia diusir dari rumah. Sekembali ke Bandung, dia menikah
dengan Kartini.
Tiga tahun kemudian,
hubungan Hasan dengan Kartini sudah memburuk. Mereka saling mencurigai.
Akhirnya, Hasan melihat Kartini meninggalkan hotel bersama Anwar dan menduga
kalau dia selingkuh - dugaan ini tidak benar. Hasan segera menceraikan istrinya
itu dan meninggalkan rumah. Tidak lama kemudian, dia jatuh sakit dengan tuberkulosis. Setelah
beberapa minggu, dia kembali ke Panyeredan karena mendengar bahwa ayahnya
sakit. Biarpun dia hendak berbaikan, ayahnya mengusir Hasan sebagai godaan
setan. Dalam keadaan putus asa, Hasan kembali ke Bandung.
Dalam keadaan sakit-sakitan,
Hasan mendekati seorang jurnalis dan menyerahkan suatu tulisan berisi riwayat
hidupnya; jurnalis ini bersedia menerbitkan karya Hasan itu bilamana terjadi
sesuatu kepada Hasan. Tak lama kemudian, Hasan keluar rumah setelah jam malam dan
tertembak oleh patroli Jepang. Dia lalu meninggal setelah disiksa, dengan kata
terakhirnya "Allahu Akbar". Hari berikutnya, Rusli dan Kartini menjemput mayatnya.
Kajian Sosiologi Novel Atheis
Latar Belakang Sosial Budaya
Ditinjau
dari sosial budaya pada hakikatnya novel Atheis menyuguhkan dua macam anggota
masyarakat yang memiliki latar belakang lingkungan hidup yang berlainan, yaitu
kelompok antarhubungan langsung (keluarga, para tetangga kampung, persekutuan
hidup kecil) dan kelompok dengan antarhubungan tidak langsung (persekutuan
hidup besar, serikat buruh, dan serikat majikan).
Dalam
roman Atheis, keluarga Raden Wiradikarta, khususnya Hasa mengambarkan kelompok
dengan antarhubungan langsung atau kelompok masyarakat yang tertutup. Gambaran
lingkunagn hidup mereka sebagai berikut:
Di lereng gunung Telaga Bodas di tengah-tengah pegunungan Priangan yang indah, terletak sebuah kampung, bersembunyi di balik hijau pohon-pohon jeru kGarut, yang segar dan subur tumbuhnya bertanah dan bahwa yang nyaman dan sejuk. Kampung Panyeredan namanya. Kampung itu terdiri dari kurang lebih dua ratus rumah besar dan kecil. Ynag kecil, yang jauh lebih besar jumlahnya dari yang besar, adalah kepunyaan buruh-buruh tani yang miskin dan yang besar ialah milik petani-petani “kaya” (artinya yang mempunyai tanah kurang lebih sepuluh hektar) yang di samping bertani, bekerja juga sebagai tengkulak-tengkulak jeruk dan hasil bumi lainnya. Di antara rumah-rumah kecil dan rumah-rumah besaar dari batu itu, ada lagi beberapa rumah yang dibikin dari “setengah batu” artinya lantainya dari tegel tapi dindingnya hanya sampai kira-kira seperempat tinggi dari batu, sedang ke atasnya dari dinding bambu biasa. (hal 16)
Sebagai anggota masyarakat kampung yang berkeadaan
serba sederhana seperti terlukis pada kutipan itu mereka memiliki kemungkinan
besar untuk memenuhi kebutuhan rohaniahnya terutama bidang religius.
Diceritakan (1926:16) “ Ayah dan ibuku
tergolong orang yang sangat saleh dan alim. Sudah sedari kecil jalan hidup
ditempuhnya dengan tasbih dan mukena.” Mereka merasa belum cukup dengan
patuh menjalankan ajaran agama yang mengandung kewajiban sehari-hari. Seluruh
hidupnya dipusatkan pada kehidupan beragama.
Mereka berguru kepada seorang Kiai di Banten untuk menjadi mistikus. “ Sebulan kemudian ayahnya memecahkan celengannya dan dengan uang yang ada di dalamnya itu berangkatlah ia ke Bnaten bersama-sama ibu.” (hal 19)
Corak
kehidupan keluarga dan lingkungannya mewarnai pendidikan yang diterima Hasan.
Sejak berumur lima tahun, Hasan memperoleh pendidkan agama yang fanatik. Dengan
kacamata ajaran agama yang fanatik banyak ahal uang dianggapnya tabu. Hasan
menjadi orang yang sempit pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Tingkah laku
Hasn pun tertuju ke arah tercapainya kebutuhan hidup di alam baka, seperti
pengakuan Hasan.
Dulu tak ada paduka kegiatan untuk mencari kemajuan di lapangan hidup di dunia yang fana ini. Segala langkah hidupku ditujukan semata-mata ke arah hidup di dunia yang baka, di alam akhirat. (hal 129)
Dengan demikian, jelaslah keadaan
sosial budaya yang melatarbelakangi kehidupan keluarga Raden Wiradikarta,
khususnya Hasan, yaitu kehiudpan sosial budaya tradisional religius. Sebagai
aggota kelompok masyarakat tertutup dengan latar belakang sosial budaya seperti
itu, ternyata Hasan (keluarga Raden Wiradikarta) tidak mampu bertahan dan
menyesuaikan diri dengan arus modernisasi.
Di pihak lain Rusli, Kartini, dan Anwar merupakan
kelompok dengan antarhubungan tidak langsung atau kelompok masyarakat terbuka.
Perhatikan riwayat hidup Rusli berikut ini:
Empat tahun Rusli hidup di Singapura. Dan selama empat tahun itu ia banyak belajar tentang soal-soal politik. Bukan hanya dengan jalan membaca buku-buku politik saja, akan tetapi juga banyak bergaul dengan orang-orang pergerakan internasional. Pergaulan semcam itu mudah sekali dijalankan di suatu kota “Internasioanl” seperti Singapura. Macam-macam aliran dan stelsel, serta ideologi-idelogi politik dipelajarinya dengan sungguh-sungguh, terutama sekali ideologi Marxisme.” (hal 36)Dari Singapura Rusli pindah ke Palembang. Di sana ia sambil berdagang, banyak menulis surat-surat kabar dengan memakai nama samaran. Kemudian ia pindah ke Jakrta, dan pada akhirnya pindah ke kota Bandung. (hal 36)
Dari kutipan-kutipan yang telah dikemukakan dapat
diketahui latar belakang sosial budaya diri Rusli. Sebagai anggota masyarakat
yang terbuka tampak Rusli telah berada dalam tingkat kebudayaan modern. Dia
memilih politik menjadi sarana untuk ikut bertanggung jawab terhadap
kelangsungan hidup masyarakat dan kebudayaan. Jelas pula kiranya, tingkah laku
Rusli diarahkan ke kepuasan hidup di alam fana ini. Akibat dari sosial budaya
moern yang menjadi latar belakang hidupnya, maka tidak ada kesulitan pada diri
Rusli untuk menyesuaikan diri dengan arus modernisasi.
Dari kelompok masyarakat terbuka diceritakan pula
adanya individu yang salah sikap dalam menerima pengaruh kebudayaan modern.
Salah satu contoh adalah penampilan diri Karetini. Diceritakan bahwa pengaruh
kebudayaan modern meresap jau dalam kehidupan Kartini. Tidak hanya itu pengaruh
kebudayaan modern pada diri Kartini. Bagi Kartini, yang kebetulan sedang
mengalami keresahan akibat kematian suaminya dan campur tangan pihak keluarga
suaminya, pengaruh modern yang dibawa oleh Rusli diterimanya tanpa seleksi.
Kartini kehilangan pribadi sebagai orang Indonesia, orang Jawa. Pergaulan bebas
tidak asing lagi baginya. Pernah ia berjalan sendiri pada tengah malam di
daerah perempuan jalang. Sudah barang tentu sikap Kartini ini minimal
menimbulkancitra bahwa Kartini seorang perempuan yang tidak baik.




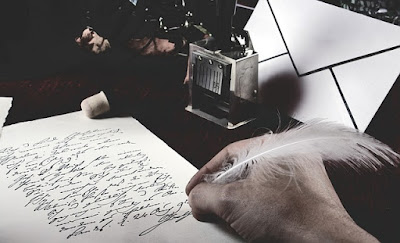
Komentar
Posting Komentar